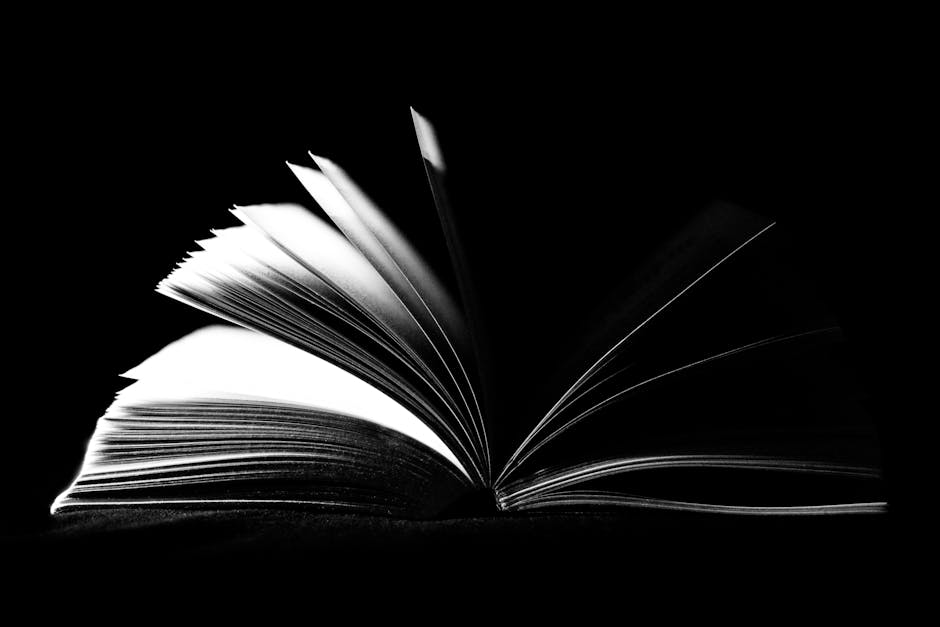Surat penerimaan dari universitas di luar negeri itu terlipat rapi di samping tumpukan tagihan yang menggunung. Aroma pahit kopi yang tersisa di udara Kedai Senja kini terasa seperti ironi; itu adalah aroma yang seharusnya kutinggalkan, namun kini menjadi belenggu yang menahan kakiku. Aku tahu, impian yang sudah kubangun sejak lama harus kukorbankan demi menyelamatkan warisan Ayah yang rapuh.
Keputusan itu terasa seperti pisau yang membelah masa mudaku menjadi dua bagian: sebelum dan sesudah tanggung jawab. Malam-malam yang seharusnya kuhabiskan untuk merayakan kelulusan, kini diisi dengan menghitung stok gula dan menghadapi ancaman penagih utang. Beban di pundakku bukan hanya soal uang, tetapi juga janji untuk menjaga martabat terakhir Ayah.
Awalnya, aku membenci tempat ini. Kedai yang dulunya ramai dan hangat kini terasa dingin, seolah ikut berduka atas kepergian pemiliknya. Aku tidak tahu cara meracik kopi yang benar, apalagi cara mengelola arus kas yang sehat; aku hanya tahu cara belajar dan bermimpi.
Namun, mata para karyawan lama yang menggantungkan hidup mereka padaku memaksa rasa benci itu berganti menjadi tekad keras. Aku belajar dari nol, mulai dari membedakan biji Arabika dan Robusta, hingga memahami trik licik para pemasok. Setiap kegagalan kecil yang kualami di balik mesin espresso mengajarkanku lebih banyak daripada semua buku teks yang pernah kubaca.
Aku sadar, semua episode sulit ini adalah babak paling krusial dalam Novel kehidupan yang harus kutulis sendiri, tanpa editor dan tanpa revisi. Aku harus menerima bahwa aku bukan lagi gadis yang hanya peduli pada nilai ujian, melainkan seorang pemimpin muda yang harus memastikan asap dapur orang lain tetap mengepul. Kehilangan ternyata adalah guru yang paling jujur dan kejam.
Pelan tapi pasti, Kedai Senja mulai bernapas lagi. Bukan karena aku jenius, tetapi karena aku belajar merangkul ketidaksempurnaan dan meminta bantuan. Aku mulai menemukan keindahan dalam rutinitas yang melelahkan, melihat wajah-wajah pelanggan yang kembali, dan merasakan getaran bangga saat aroma kopi racikanku dipuji.
Pendewasaan ternyata bukanlah soal bertambahnya usia, melainkan tentang seberapa cepat kita mampu menggeser fokus dari "apa yang kuinginkan" menjadi "apa yang harus kulakukan." Aku menukar kebebasan dengan kedewasaan, dan ternyata, harga yang kubayar itu sepadan dengan kekuatan batin yang kuperoleh.
Aku mungkin tidak mendapatkan beasiswa itu, tetapi aku mendapatkan hal yang jauh lebih berharga: kepercayaan diri bahwa aku bisa bertahan di tengah badai. Aku berdiri tegak di balik meja kasir, bukan lagi dengan rasa terpaksa, melainkan dengan rasa memiliki yang mendalam.
Kini, setiap kali aku mencium aroma kopi pahit itu, aku tidak lagi mencium kegagalan, melainkan ketahanan. Namun, di sudut hatiku, masih ada secercah pertanyaan yang tak pernah hilang: apakah Ayah akan bangga dengan diriku yang sekarang, ataukah ia akan sedih melihat impian besarku terkubur di balik cangkir-cangkir kopi?

.png)
.png)